Cerpen Noor H. Dee
Suara Karya, Minggu, 4 Juni 2006
Di tempat inilah aku menunggu wanita itu. "Tunggu aku di tempat biasa. Jam setengah lima, setelah aku pulang kerja. Jangan sampai terlambat, ya." Begitulah bunyi pesan pendek yang ia kirimkan ke telepon genggamku. Karena aku mencintainya, tentu saja permintaannya itu langsung aku turuti. Sepulang dari tempatku bekerja, aku langsung bergegas menuju tempat ini dan menunggu kedatangannya. Sendirian.
Memang, kami memang biasa bertemu di tempat ini, sebuah tempat yang tidak bisa dikatakan sebagai tempat yang istimewa. Tempat ini hanyalah sebuah halte. Tempat persinggahan untuk sementara waktu. Seperti sebuah kehidupan, begitu pikirku. Ya, halte memang seperti sebuah kehidupan. Tempat yang cuma disinggahi sebentar. Tidak bisa untuk tetap tinggal abadi. Hanya sementara waktu, untuk kemudian kembali melanjutkan perjalanan berikutnya yang entah menuju ke mana dan entah akan berakhir di mana.
Aku menatap arloji digital yang memeluk pergelangan tangan kananku. Angkanya menunjukkan pukul 16:00. Hmm, rupanya aku datang lebih awal setengah jam. Biarlah. Setidaknya aku tidak datang terlambat. Lagi pula, setengah jam bukanlah waktu yang lama. Cuma tiga puluh menit. Apalagi untuk menunggu seorang wanita seperti dia. Menunggu sampai bertahun-tahun pun akan kujalani. Menunggu sampai menjadi patung pun akan kusanggupi. Bukankah cinta butuh pengorbanan? Dan menunggu, seperti kita tahu, juga termasuk dari sebuah pengorbanan, bukan? Aku mencintainya. Dia juga, katanya, mencintaiku. Jadi, tak ada salahnya kan jika aku mengorbankan setengah jam hidupku hanya untuk menunggu wanita itu?
Jress! Aku menyalakan sebatang rokok yang terselip di antara celah bibirku. Sekepul demi sekepul asap rokok meluncur ke udara dan segera melarut bersama angin sore. Di hadapanku, segala jenis kendaraan berlalu-lalang. Sepeda motor menyalip bis kota. Sedan hitam mendahului taksi. Debu-debu saling berkejaran. Aku mengembuskan asap rokok ke udara. Seorang wanita muda turun dari bus Patas, lantas berjalan perlahan menuju halte ini dan duduk di sampingku. Aku melirik ke arahnya. Wajahnya cantik. Rambutnya yang bergelombang itu dibiarkannya tergerai. Di mataku, ia terlihat seperti seorang wanita yang tahu betul betapa pentingnya arti sebuah penampilan. Aku menarik nafas panjang, dan dengan segera aroma parfum yang meruap dari tubuhnya itu langsung masuk ke dalam hidungku. Hmm. Aku melirik ke arah matanya. Tetapi, hei, mengapa matanya terlihat begitu sedih? Apakah ia sedang terluka?
Aku mendengar suara telepon genggam berbunyi. Nadanya terdengar asing di kedua telingaku. Tentu, tentu suara itu milik telepon genggam wanita itu. Dari ekor mataku, aku melihat wanita itu membuka tasnya yang berukuran kecil, mengambil sebuah telepon genggam yang kecil, lantas didekatkan di telinga kanannya yang tergantung anting-anting yang juga kecil. Aku mendengar ia berbicara.
"Sudahlah, lupakan aku. Selamat tinggal."
Kemudian, aku melihat ia mematikan telepon genggamnya dan menatap kosong ke depan.
"Apakah setiap laki-laki memang seperti itu?" tanyanya lirih. Entah kepada siapa.
Aku tidak menjawab, sebab ia memang tidak bertanya kepadaku. Kalau pun ia memang bertanya kepadaku, tentu aku butuh waktu untuk bisa menjawabnya. Sebab, pertanyaannya itu memang tidak akan cukup jika cuma diberikan jawaban 'iya' atau 'tidak'.
Aku masih tetap memerhatikan wanita cantik itu. Setelah menaruh telepon genggamnya, ia mengambil sebatang rokok dari dalam tas kecilnya, menyelipkannya di celah bibirnya yang berwarna merah, mambakarnya, menyemburkan asapnya secara sembarang, lantas berdiri dan berjalan meninggalkan halte ini. Ia seperti tidak mempedulikan akan keberadaanku. Ia seperti berada di sebuah dimensi kosong yang tidak ada orang lain lagi kecuali dirinya sendiri. Kedua mataku, entah mengapa, masih terus membututinya. Ia berjalan di atas trotoar, sambil terus merokok, dan melenyap di sebuah kelokan. Ke manakah wanita itu akan pergi? Entahlah. Tentu saja aku tidak akan pernah tahu. Misteri.
Aku kembali mengembuskan asap rokokku ke udara. Terkadang asap itu kupermainkan, agar aku tidak jemu dalam penantian. Aku memonyongkan bibirku, mendesak asap itu dengan lidahku, lantas meluncurlah segumpal asap yang membentuk sebuah lingkaran. Sebuah lingkaran putih, seperti lingkaran yang selalu mengambang di atas kepala malaikat yang sering kulihat di komik-komik. Aku bisa melihat bagaimana asap itu melayang, mengambang, lantas menghilang karena dihapus angin. Segumpal asap, begitulah, meskipun terlihat sepele, ternyata bisa memberikan ketenangan bagi diriku.
Ke manakah wanita itu akan pergi? Aku kembali bertanya tentang wanita yang telah lenyap di kelokan itu. Barangkali ia akan pergi ke sebuah tempat yang belum pernah ia kunjungi. Namun, di manakah tempat itu berada? Tentu saja cuma wanita itu yang mengetahuinya. Barangkali ia akan mengunjungi sebuah tempat yang dapat menghadirkan kebahagiaan semu. Seperti diskotik, pub, atau pun kafe-kafe yang lampunya selalu remang-remang, yang seperti enggan menghadirkan sebuah kenyataan. Tetapi, ah, sepertinya itu tidak mungkin. Hari masih sore, dan sore bukanlah waktu yang tepat untuk pergi ke tempat-tempat semacam itu. Barangkali ia akan pulang ke rumah. Tidak pergi ke mana-mana. Sebab, ia berpikir, pergi ke mana-mana pun tidak akan mampu menghibur hatinya yang anggap saja sedang terluka itu. Ia akan berdiam diri di dalam kamar. Barangkali ia akan menangis, dan menghabiskan waktunya hanya dalam kesendirian. Dan, ia akan tersadar, betapa di dunia ini tidak ada yang tetap tinggal abadi.
Hmm. Aku kembali teringat dengan wanita yang saat ini sedang kutunggu-tunggu kehadirannya. Apakah ia juga akan seperti itu jika hatinya sedang terluka? Apakah ia juga akan mengatakan, 'Apakah setiap laki-laki memang seperti itu?' jika hatinya telah dikhianati? Hmm. Aku jadi semakin tidak sabar dan ingin cepat-cepat bertemu dengannya.
* * *
Di tempat inilah aku menunggu wanita itu. Aku membuang rokokku yang sudah pendek ke aspal dan membunuh baranya dengan injakan. Fiiuuuh! Segumpal asap terakhir meluncur dari bibirku. Lima belas menit sudah berlalu. Berarti, lima belas menit lagi, ia akan hadir di hadapanku. Aku memang sudah terbiasa menghitung waktu dengan sebatang rokok. Sebatang rokok, bagiku, bisa menghabiskan waktu kurang lebih lima belas menit. Langit di atas sana memperlihatkan pemandangan sore. Mega-mega bersepuh susu berarak lambat melintasi cakrawala mengikuti ajakan angin. Matahari bersembunyi di balik gedung-gedung kaca. Angin berembus. Daun-daun saling menampar. 'Lima belas menit lagi,' ujarku dalam hati.
Wanita yang sedang kutunggu-tunggu kehadirannya itu adalah seorang wanita yang menarik. Memang tidak cantik, tetapi menarik. Ah. Cantik. Menarik. Manakah yang lebih menjanjikan untuk sebuah kebahagiaan?
"Aku tidak cantik," ujarnya dulu.
"Lantas, memang kenapa kalau tidak cantik?"
"Iya, mengapa kamu memilih aku? Bukankah masih banyak yang lebih cantik dari aku?"
"Aku memilihmu, sebab kamu adalah wanita yang menarik."
"Menarik?"
"Ya, menarik."
"Tapi, aku tidak cantik."
"Tidak perlu harus menjadi cantik, untuk bisa tampil menarik."
"Kalau begitu, apa yang menarik dariku?"
"Matamu."
"Mataku? Ada apa dengan mataku?"
"Seperti ada tali."
"Maksudmu?"
"Ya, di dalam matamu seperti ada tali yang telah menarik hatiku sehingga membuatku jatuh cinta kepadamu."
"Uh, gombal!"
Hmm. Gombal. Aku masih belum mengerti mengapa segala bentuk pujian yang dikatakan secara jujur pun masih tetap dikatakan gombal? Apakah setiap kata-kata yang manis, yang diucapkan dengan sebenar-benarnya dari dalam hati, masih juga tetap dikatakan gombal? Hmm. Gombal. Makhluk apakah itu?
Halte ini kebetulan sepi. Hanya aku saja duduk di sini, sendirian, menunggu wanita itu, tanpa ada teman yang mengawani. Menyaksikan pemandangan sekitar. Menyaksikan dunia. Apa boleh buat, ternyata memang benar perkataan orang bijak itu, betapa dunia cuma sebatas mata memandang. Aku melihat sebuah bis kota yang penuh sesak dengan penumpang. Laki-laki. Perempuan. Anak kecil. Orang tua. Mereka yang berada di pintu itu bergelantungan dengan berbagai macam cara, bertahan sekuat mungkin agar tidak sampai terjatuh. Mereka yang berada di dalam sana terlihat lebih memrihatinkan. Tubuh-tubuh mereka saling terhimpit satu sama lain. Aku bisa membayangkan betapa sumpek di dalam sana. Namun, sang kernet dengan wajah tanpa dosa masih terus menawarkan jurusan kepada setiap orang yang sedang berada di pinggir jalan. Seandainya aku juga berada di dalam sana, betapa jengkelnya aku melihat aksi sang kernet itu.
Aku kembali melirik arloji digitalku. Angkanya menunjukkan pukul 16:20. Berarti, sepuluh menit lagi wanita itu akan hadir di hadapanku. Aku membayangkan apakah kiranya yang akan kami lakukan jika bertemu nanti. Barangkali ia akan langsung mengajakku makan di sebuah tempat. Sama seperti yang biasa kami lakukan setiap kali bertemu. Kalau tidak di restoran Jepang, pastilah ia akan memilih makan di restoran siap saji. Aku juga tidak mengerti mengapa ia suka sekali makan di tempat-tempat semacam itu. Aku pernah mengusulkan untuk sekali-sekali makan di restoran padang. Tetapi ia selalu menolaknya. "Aku tidak mau. Aku lebih suka makan di sini." Begitulah jawabannya selalu.
Jika memang benar kami makan, maka kami akan makan secara perlahan, sengaja agar pertemuan terasa lama. Tetapi, entah mengapa, itu tidak pernah berhasil. Aku selalu merasa pertemuan kami selalu cepat berakhir. Setiap kali kami bertemu, aku selalu merasa waktu begitu cepat melesat. Satu hari bersamanya, sama seperti satu jam. Satu jam, terasa satu menit. Entahlah, aku juga tidak mengerti mengapa selalu seperti itu.
Seperti biasa, kami akan makan sambil bercerita tentang banyak hal. Sebenarnya ia yang lebih banyak bercerita, dan aku yang lebih banyak mendengarkan. Tentang pekerjaannya yang melelahkan. Tentang atasannya yang menjengkelkan. Tentang teman-teman pria di kantornya yang sering menggodanya. Tentang cinta. Tentang harapan. Tentang mimpi-mimpi. Tentang apa saja. Tentang siapa saja. Juga tentang hal-hal yang kelihatannya sepele, namun tetap memiliki daya tarik untuk dibicarakan. Tentang dedaunan, langit malam, sepotong senja, dan lain semacamnya yang sebenarnya memang tidak terlalu penting-penting amat. Biasanya, ia akan bercerita dengan mata berbinar-binar. Semakin berbinar-binar matanya, semakin aku jatuh cinta dibuatnya. Matanya itu, ya, matanya itu seperti sebuah jendela yang menampilkan seribu pemandangan bukit, seribu pemandangan laut, seribu pemandangan semesta, sehingga membuat aku betah untuk berlama-lama menatapnya. Matanya, ya, matanya yang sejernih telaga itulah yang membuat aku benar-benar jatuh cinta kepadanya.
"Matamu indah," ujarku dulu, entah kapan dan di mana, aku sudah lupa. Yang bisa kuingat, saat itu ia cuma mengulas senyum sambil menarik kepalaku mendekati kepalanya. Lantas, ia menjepit bibirku dengan bibirnya sambil berkata, "Aku mencintaimu, laki-laki gombal."
* * *
Di tempat inilah aku menunggu wanita itu. Arloji digitalku sudah menunjukkan pukul 16:40. Ia belum juga hadir di hadapanku. Apakah suaminya datang menjemput? Hmm. Terkadang aku lupa betapa ia adalah seorang wanita yang sudah bersuami. Sekarang ia belum datang. Alasannya apa, aku belum tahu.
Tiba-tiba telepon genggamku berbunyi dan bergetar di saku celana. Aku meraihnya. Ada pesan yang masuk. Ternyata dari wanita itu. Hmm. Apakah ia ingin membatalkan pertemuan ini? Atau, apakah ia akan datang terlambat, sebab ada sesuatu hal yang mesti ia kerjakan di kantornya?
Aku menarik nafas panjang dan segera membuka kotak pesan di layar telepon genggamku.
Aku membaca sebuah pesan. "TAMAT"
Baca cerpen lainnya
Label:
CERPEN,
FIKSI DEWASA,
NUKILAN
Related Posts:
Langganan:
Posting Komentar (Atom)















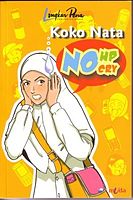
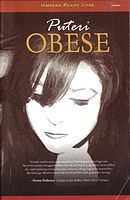
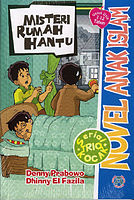


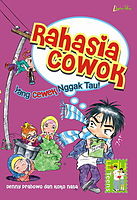


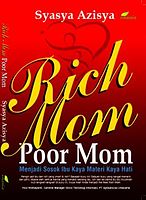

0 komentar:
Posting Komentar