
Cerpen Denny Prabowo
Suara Pembaruan Minggu, 30 Juli 2006
Sebuah kereta kencana beroda empat bermesin Mercy meluncur memburu sisa hujan yang jatuh di sebuah telaga bintang tujuh. Aku berjalan menyusuri jejak roda yang ditinggalkan di atas aspal jalanan, untuk sampai diam-diam ke telaga itu sebagai bayangan. Udara menyimpan aroma mesum dari balik gerbang pemandian telaga itu. Sesaat lagi pelangi mengurai warna-warni. Kusiapkan belati. Untuk menyambut upacara suci, yang ditandai dengan datangnya perempuan-perempuan serupa bidadari ke telaga itu. Hari ini dongeng itu harus segera kulenyapkan. Hari ini harus aku rebut apa yang telah dia curi dari ibuku!
***
Sebait puisi, sekepul kopi, membuka hari. Senja menghitung usia. Belum cukup tua. Raut melayunya masih menawarkan cahaya keemasan. Belum waktunya malam menumpahkan tinta hitam di wajah keemasannya. Selalu. Setiap pagi. Senja duduk di beranda depan rumahnya menikmati cahaya matahari yang menerobos celah rerimbun ranting pepohonan yang tumbuh di pekarangan rumah. Menikmati secangkir kopi, sambil menulis sebait puisi di secarik kertas yang disobek dari buku diari, sebelum diremas-remas untuk kemudian dilemparkan begitu saja ke dalam tempat sampah yang diletakkan tak berapa jauh dari kursi tempat duduknya. Sebagian terserak mengelilingi bak sampah. Puisi yang sama dengan pagi-pagi sebelumnya.
Matahari sepenggala. Senja belum beranjak dari tempat duduknya. Kopi dalam cangkir telah tak bersisa. Secarik kertas bertulis sebait puisi terkapar di atas meja kayu tertindih pena. Entah kertas ke berapa yang dia sobek dari diarinya untuk ditulisi sebait puisi. Angin bersiut. Ujung kertas itu terangkat ke udara. Senja memejam mata. Mungkin terlelah. Menunggu angin membawa musim penghujan.
Suara rintik di atas atap rumah. Gegas Senja membuka mata. Hanya sekejap saja. Gerimis tak jadi hujan. Senja mendesah. Membuang kecewa. Sebulir air menggantung di ujung matanya. Ada kabut di sana. Tertunduk Senja sebelum kembali merebahkan tubuhnya di kursi kayu. Kembali memejam mata. Telah lama dia berharap pada hujan. Hanya hujan yang mungkin mengantarkannya pada Pelangi. Lelaki yang telah menjadi pelabuhan cintanya. Lelaki yang telah mencuri selendangnya ketika Senja sedang mandi di telaga bersama para bidadari.
“Tak usah kau cari selendangmu itu!” ujar Pelangi, saat Senja berputus asa karena tak berhasil menemukan selendangnya yang telah hilang. Entah siapa yang mencurinya. Sedang waktu tak lagi mau menunggu. Sudah waktunya meninggalkan telaga. Kembali ke negeri asal para bidadari.
“Mengapa?” ujar Senja takjub, menatap dengan mata tak berkedip ke arah Pelangi yang bagai memancarkan beragam warna terindah.
“Selendang itu ada di hatiku. Kau tak lagi membutuhkannya untuk kembali ke negerimu. Sebab aku akan memindahkan negeri itu untukmu.”
“Kau tidak sedang membual?”
“Percayalah padaku.”
“Siapa kau?”
“Aku Pelangi,” Lelaki bertubuh tegap itu memperkenalkan dirinya. Angin sore menerbangkan ujung-ujung rambutnya yang tergerai hingga sebatas bahunya yang jenjang.
Sejak itu selalu ada hujan dalam kehidupan Senja. Sebab hanya hujan saja yang bisa menghubungkannya dengan Pelangi. Seolah-olah hujan itu memang diciptakan untuknya. Meski tak sebenderang matahari, walau tak secemerlang bintang-bintang, Pelangi mampu memberikan warna-warni dalam kehidupan Senja. Senja benar-benar telah melupa selendangnya. Dia tak lagi ingat negeri asalnya. Meski hidup serba seadanya. Warna-warni yang diberikan Pelangi mampu membuat Senja bahagia.
Lalu.
Seorang anak lahir dari buah pernikahan mereka. Diberinya nama Awan, seorang bocah lelaki, melengkapi kesempurnaan. Tapi adakah yang sempurna selain Tuhan? Semula Senja berharap Awan akan selalu mengirimkan hujan, sehingga selalu ada alasan bagi Pelangi untuk kembali menampakkan warna-warni. Sebuah harapan yang terkabulkan. Suara tangis Awan seperti pertanda datangnya hujan. Semacam undangan bagi Pelangi untuk selalu memainkan warna-warninya.
Pelangi sungguh lelaki yang sempurna, begitu setidaknya yang sempat Senja duga. Tidak seperti lelaki lain yang enggan bersentuhan dengan ompol bayi dan bau tai anaknya. Malam-malam ketika Senja harus terjaga, manakala bayi mungilnya menangis karena haus atau harus diganti popoknya, Pelangi selalu menemaninya. Terkadang bahkan lelaki itu yang mengerjakan semuanya, kecuali menyusui bayi tentunya. Sesibuk apa pun Pelangi, dia selalu memiliki waktu untuk Senja dan anaknya.
Dedaunan kering jatuh. Berguguran. Musim penghujan belum menampakkan batang hidungnya. Meski sudah masuk bulannya. Hanya sesekali rintik. Jatuh untuk beberapa puluh detik. Tak pernah jadi hujan. Senja masih menyimpan harapan pada Awan, memekat hitam menaungi atap rumah, mengirimkan hujan lewat tangisan meski hanya sesaat, dan matahari akan mengurai warnanya pada butiran embun, pada saat itulah Pelangi biasanya menampakkan diri. Tapi Awan seperti enggan memenuhi harapan bundanya. Awan sudah terlalu dewasa untuk dipaksa mengeluarkan air mata. Meski itu patut dilakukannya, tersebab melihat bundanya yang menderita dalam penantian.
Senja membuka mata. Sinar matahari pukul dua belas menyentuh kulit Senja yang keemasan. Tak sampai membakar. Reranting daun yang meski kering namun merimbun sedikit meredam. Senja melirik meja kayu di sebalahnya. Ada sepiring makan siang di samping kertas bertulis puisi yang tertindih pena. Pasti Awan yang meletakkannya di sana, begitu pikirnya. Senja tersenyum. Dia mengangkat piring itu. Membenam beberapa suapan ke dalam mulutnya, sebelum kembali meletakkannya di atas meja. Dia mengambil kertas bertulis puisi yang tertindih pena, meremasnya, untuk kemudian melemparnya ke tong sampah. Kali ini tepat masuk ke dalamnya. Senja merobek kertas lain dari diarinya. Jemari lentiknya menggoyang pena, menari di atas kertas. Sebait puisi tercipta. Puisi yang sama. Beberapa lama Senja memandangi puisinya, sebelum meremas, dan melemparkannya ke dalam tong sampah.
Pandangan Senja menerawang, mungkin berusaha menangkap bentangan kisah yang terekam dalam memori otaknya, di mana Pelangi menjadi pemeran utama dari setiap lakon yang tersimpan di sana. Mungkin dia teringat pada hujan terakhir yang dikirimkan Awan lewat tangisan, ketika Pelangi untuk yang terakhir kali memancarkan warna-warni terindah lewat ciuman termesra, sebelum pergi meninggalkan rumah, dan tak pernah kembali menampakkan muka. Ketika itu Awan masih terlalu hijau untuk mengerti yang terjadi.
Baru setelah bangku menegah pertama didudukinya, Awan tahu mengapa Pelangi tak pernah menampakkan warna-warninya lagi di rumah, meski dia coba memberikan tangisan tersedih, hingga gelap menaungi wajah, tak juga mampu mendatangkan hujan yang menjadi alasan bagi Pelangi menampakan warna-warni selama ini.
Kehadiran Senja dalam kehidupan Pelangi merubah garis nasib yang selama ini harus dia jalani sebagai karyawan kelas bawah sebuah telaga bintang tujuh. Sebagai perempuan negeri atas awan, Senja memiliki kemampuan memutar roda pedati milik Pelangi, hingga arah nasib berada di atas. Gubuk bersulam derita itu menjelma istana serupa tempat pengeran yang meminang Cinderella berumah tinggal. Semua mungkin dilakukannya tersebab orangtua Senja penguasa negeri atas langit, yang meski berkeberatan atas pernikahan Senja dengan Pelangi tapi tak juga rela melihat anaknya menderita hidup dalam gubuk bersulam derita. Kini Pelangi tidak saja telah naik jabatan, tapi telah menjelma menjadi pemilik telaga bintang tujuh yang tersebar hampir di seluruh penjuru mata angin. Sejak itu Pelangi seolah tak memiliki waktu untuk memainkan kembali warna-warninya. Segala upaya telah dilakukan Awan untuk menurunkan hujan, tapi sepekat apa pun wajah Awan, tak mampu mencipta hujan terderas yang memungkinkan matahari mengurai warnanya pada butiran embun untuk menghadirkan sosok Pelangi.
“Mengapa bunda masih saja menantinya?” gugat Awan setelah tahu, alasan Pelangi tak memiliki waktu untuk Senja dan dirinya.
“Karena dia memiliki selendangku.”
“Tapi Bunda berhak untuk bahagia.”
“Kebahagiaanku hanya jika Pelangi menampakan warna-warni terindahnya.”
“Bunda masih berharap kepadanya?”
“Lebih dari sekedar berharap.”
“Meski hanya kesia-siaan yang mungkin Bunda dapatkan?”
“Tak ada yang sia-sia dalam hidup ini.”
“Tidak kah Bunda merasa kalau lelaki yang Bunda nanti telah pula mencuri selendang bidadari lain?”
Senja tak membuka suara. Kemungkinan yang baru saja Awan sampaikan sudah lama mengendap dalam kepalanya. Bukan tanpa sebab hujan seperti enggan membelai tanah tempat Senja memijak kaki. Sedang di lain tempat, hujan rajin menyapa kerinduan retak tanah musim kemarau. Senja tertunduk menenggelamkan wajahnya. Sinar keemasannya sedikit meredup. Awan tak lagi merasa perlu bertanya.
Angin menggoyang kenangan, helai-helai daun kering terlepas dari rantingnya, melayang-layang, sebelum mendarat menyesak rerumput hijau di pekarangan rumah Senja. Matahari meninggalkan singgasana meniti tangga cahaya, bersiap menenggelamkan diri ke balik tebing cakrawala. Senja mengambil buku diarinya, menyobek secarik kertas, sebelum menorehkan larik puisi di atasnya. Sesaat Senja memandangi puisi itu. Puisi yang sama dengan yang ia tulis di atas kertas yang kini menghuni tong sampah dan sebagian terserak di sekitarnya karena lemparannya tak tepat. Senja belum beranjak dari kursi tempat duduknya. Ia menyandarkan kepalanya pada sandaran kursi, menenggelamkan carik kertas bertulis puisi ke dalam dekapannya. Matanya menawan mega yang arak berarak, sebelum sepasang bulat telur itu memejam.
Aku meletakkan sebelah lututku di atas lantai, bersimpuh di depan kursi tempat Senja duduk sejak tadi. Pelan-pelan aku melepaskan carik kertas dari dekapan Senja, agar tak terganggu tidurnya. Aku melepas jaket yang kukenakan, membentangkan di atas tubuhnya. Angin berembus semakin kencang.
Aku baru saja memalingkan tubuh hendak melangkah meninggalkannya, setelah mendaratkan kecupan di keningnya yang tersembunyi di balik lebat poni rambutnya, ketika Senja membuka suara, membuat aku mengurungkan langkah.
“Awan...”
Aku memutar tubuh. Tersenyum menatapnya. Kutemukan harapan terbit di kerling matanya. Ia beranjak dari kursi tempat duduknya.
“Apakah ayahmu sudah kembali?”
Ah, haruskah kukatakan kepadanya, kalau jauh sebelum kokok ayam membangunkan matahari dini hari tadi, aku telah menancapkan belatiku di dada Ayah, untuk mengambil selendang yang dulu pernah dia curi dari Bunda?
Rumah Cahaya Depok, 03/05/06















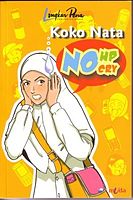
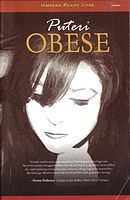
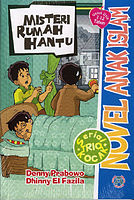


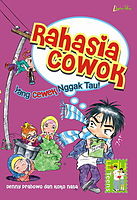


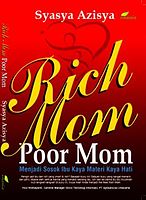

0 komentar:
Posting Komentar